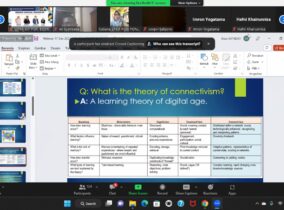Mbah Iyem

Mbah Iyem, perempuan renta sebatang kara yang tinggal di gubuk reot hampir rebah dan tanpa listrik, terheran-heran kala sejumlah penduduk miskin mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Kepada salah seorang tetangga yang mendapatkan bantuan dia bertanya dalam bahasa Jawa karena dia tidak paham bahasa nasional, “Kenapa ya aku malah tidak dapat?”
“Bukannya dulu sudah diumumkan kalau Mbah disuruh ke Balai Desa untuk mengisi formulir dan buat tanda tangan? Salah Mbah sendiri tidak datang. Ya, bantuan untuk Mbah tidak keluar.”
Bukannya Mbah Iyem tidak mau datang ke Balai Desa, tetapi dia memang tidak sanggup berjalan jauh ke ujung desa karena sudah lemah dan sering sakit-sakitan. Selain itu, karena buta huruf, dia sama sekali tidak bisa mengisi formulir. Jangankan menulis, tanda tangan saja dia tidak mengerti.
***
Dulu, semasa mudanya, Iyem adalah pembuat tempe dan menjualnya sendiri dengan berjalan kaki sambil memikul bakul ke pasar-pasar dari Ngrayun sampai Slahung yang jaraknya lebih 20 km. Seumur hidupnya dia tidak pernah naik angkot yang memang jarang melintas di jalan berbatu naik-turun pengunungan di desa pelosok yang dipenuhi pohon pinus dan mahoni milik pemerintah.
Iyem begitu semangat berjualan karena tempe penuh sebakul yang digendongnya habis terjual petang harinya. Tempenya terkenal lembut dan enak. Tidak seperti tempe-tempe orang lain atau tempe-tempe zaman sekarang yang keras dan ada pahitnya. Sekarang—mungkin juga dulu—sulit menemukan tempe yang benar-benar empuk seperti buatan Iyem.
Kesehariannya disibuki dengan mengurus rumah, mengolah kedelai, dan berjualan. Semua itu dilakukannya sendiri, bahkan ketika Semprul menikahinya. Malah, saat bersuami beban hidupnya semakin bertambah berat. Selain mengurus rumah, membuat tempe, dan menjualnya, dia juga harus mengurus anak, ditambah mengurus suami yang pemalas.
Bisa dibilang, sepanjang hidup yang diberikan Tuhan, Semprul hampir tidak pernah memberikan nafkah dan tidak peduli pada anak lelakinya. Terlebih, suaminya yang mata keranjang dan suka ilmu perdukunan itu kepincut perempuan lain, dan pergi meninggalkan Iyem begitu saja. Sampai sekarang, sekalipun suaminya sudah tujuh tahun lalu meninggal, Iyem tetap sakit hati.
Semprul meninggal secara tidak wajar. Banyak orang desa berkeyakinan bahwa suami Iyem meninggal karena guna-guna dari dukun yang menjadi lawannya. Saat meninggal Semprul muntah darah. Darah itu tidak saja keluar dari mulutnya, melainkan juga dari hidung. Menurut saksi mata, dalam darah yang dimuntahkan Semprul itu terdapat banyak jarum dan remah paku.
***
Sungguh mustahil, Mbah Iyem yang tidak diberikan uang belanja oleh suaminya yang menikahi perempuan lain, bisa memiliki sebidang kecil tanah dan mendirikan rumah mungil sendiri kalau dia tidak bekerja sangat keras. Dia adalah perempuan tangguh di masa mudanya yang begitu menikmati sebagai seorang pembuat tempe dan merasa sangat bahagia ketika orang-orang menyerbu barang dagangannya.
Dia bekerja siang malam sendirian—benar-benar siang malam dan benar-benar sendirian—sehingga dia bisa membesarkan Parmin, anak lelakinya. Kini Parmin yang hanya mampu disekolahkan sampai kelas tiga sekolah dasar, telah lama pergi merantau. Jangankan mengirimkan uang, kabar saja tidak pernah datang. Entah masih hidup atau sudah meninggal, Mbah Iyem tidak tahu. Namun, setiap malam, dia terus resah memikirkan nasib anaknya itu di perantauan. Setiap malam, selama tiga puluh tahun lebih setelah kepergian Parmin yang entah merantau ke mana.
Seandainya saja Parmin tidak pergi merantau, tentu nasib Mbah Iyem tidak separah ini. Di usia sekarang, yang dia sendiri tidak tahu kapan tahun lahirnya, dengan wajah keriput, mata cekung, jalan terbungkuk-bungkuk, dan lutut yang rematik, hampir tidak mampu berbuat apa-apa, selain mencari kayu bakar dan memasak makanan alakadar agar dirinya bisa bertahan hidup.
Setelah tidak mampu lagi membuat dan berjualan tempe, untuk bertahan hidup, Mbah Iyem menanam kunyit dan jahe di lahan sempit perkarangan rumahnya. Sebidang kecil tanah yang dibelinya dulu dengan susah payah mengumpulkan uang setelah suaminya minggat dengan perempuan lain, yang tanah itu semakin sempit setelah dibangun gubuk mungil, Iyem merasa bersyukur karena di hari tuanya sekarang dia memiliki tempat tinggal dan tidak terlunta-lunta sekalipun hidupnya sangat miskin.
Setahun sekali, ada pedagang keliling yang singgah memetik buah alpukat dari dua pohon yang ditanam di halaman depan rumahnya. Uangnya diirit-irit untuk membeli beras, tahu, dan tempe. Sayangnya, tahun ini alpukatnya tidak banyak berbuah, hasil dari jahe dan kunyit sangat sedikit, terlebih harganya yang terlalu murah. Dia betul-betul kesusahan. Boleh dibilang, orang paling miskin di desa itu adalah dirinya. Namun sungguh aneh, malah dirinya yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah.
Hari ketika pemerintah desa membagikan bantuan beras kepada penduduk miskin, dengan jalan terbungkuk-bungkuk sambil menahan nyeri di pinggang dan lututnya, Mbah Iyem mendatangi tetangga yang menerima bantuan sambil bertanya kenapa dirinya tidak mendapatkan bantuan serupa. Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada Kepala Dusun yang rumahnya berada di balik bukit.
Napas Mbah Iyem tersengal-sengal ketika dia bertanya dalam bahasa Jawa, “Kenapa aku bisa tidak dapat beras?”
Dengan berat dan penuh penyesalan si Kepala Dusun setengah baya yang memasang sikap wibawa itu menjawab, “Bantuan kali ini tidak bisa diwakilkan, Mbah. Mbah sendiri yang tidak mengisi formulir dan tidak ada tanda tangan. Jadi, bantuan untuk Mbah tidak keluar. Bantuannya dialihkan.”
“Dialihkan?” tanya Mbah Iyem tidak mengerti.
“Iya, Mbah,” jawab Kepala Dusun, “dialihkan.”
“Dialihkan bagaimana?”
“Ya dialihkan untuk orang lain.”
“Dialihkan untuk orang lain bagaimana?”
“Ya orang lain yang menerimanya.”
“Aku tidak dapat?”
Kepala Dusun menghela napas, “Iya, Mbah. Mbah tidak dapat.”
Mbah Iyem tampak sedih. Wajah keriputnya tampak lebih keriput dan mata cekungnya berkaca-kaca.
***
Seandainya saja Parmin yang pernah duduk tiga tahun di sekolah dasar ada bersamanya, tentu dia bisa membantu membawanya ke Balai Desa untuk mengisi formulir dan mengajarinya membuat tanda tangan, sehingga Mbah Iyem bisa mendapatkan beras dan sekilo telur ayam. Namun, Parmin entah di mana sekarang. Kalau dia masih hidup, tentunya dia sudah kawin dan punya anak. Mungkin juga anaknya sudah tumbuh remaja.
Sekarang Mbah Iyem hanya bisa mengurut dada. Dia sungguh tidak mengerti dengan peraturan pemerintah yang, tentunya, dibuat oleh orang-orang yang bersekolah tinggi. Dan hanya orang-orang yang bersekolah yang mampu memahaminya. Mbah Iyem tidak pernah sekolah karena zaman dia kecil dulu belum ada sekolah di desanya dan orangtuanya hidup sangat miskin sebagai petani, sekalipun sering memohon kepada arwah-arwah leluhur dengan memberikan sesajen.
Ya sudah, batin Mbah Iyem. Beras bantuan itu bukan rezeki miliknya, melainkan milik orang miskin lain. Rezeki miliknya adalah yang berasal dari keringatnya sendiri. Sekarang tubuhnya sudah tua dan lemah, tidak bisa mengeluarkan keringat seperti dulu lagi. Dia hanya bisa tabah menjalani hidup yang dirasanya tidak akan lama lagi. Namun, sama sekali dia tidak gundah apalagi takut menghadapi kematian.
Kepada tentangga terdekat dia menitip pesan, “Nanti kalau aku tidak keluar-keluar dari gubukku, kalian masuk saja. Pintunya tidak pernah aku kunci lagi.” []
Ponorogo, 12 September 2020
ARAFAT NUR adalah dosen Bahasa dan Sastra di STKIP PGRI Ponorogo. Novel Lampuki (Gramedia, cetak ulang 2019) meraih Kusala Sastra Khatulistiwa 2011 dan memenangkan sayembara DKJ 2010. Buku kumpulan cerpen terbarunya Serdadu dari Neraka (Diva Pres, 2019) sudah beredar luas.
Cerpen ini telah terpublikasi di cendananews.com pada 11 September 2021
Sumber : Cendana News