[Cerpen] Puisi di Dada Temanku
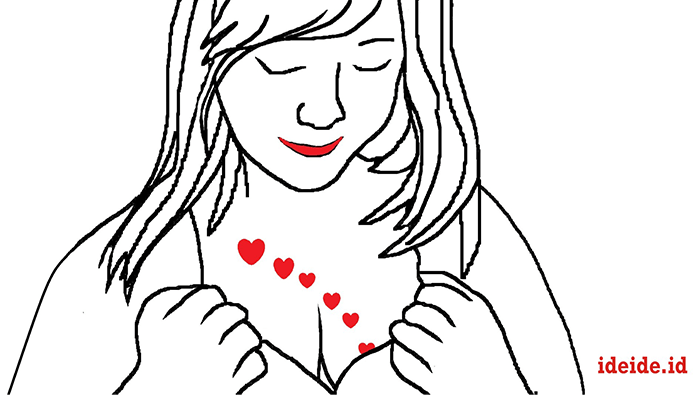
Cerpen: Sri Wahyuni
“Kau sudah mengatuk?” tanyaku.
“Tidak adakah pertanyaan yang lebih penting?”
“Tidurlah jika kau mengantuk.”
“Jika aku tidur, apakah kau akan berhenti bercerita?”
“Tidak. Aku akan tetap bercerita sambil membelai rambutmu sesekali juga dadamu.”
Temanku pernah bercerita tentang kekasihnya dan sebuah puisi, Baruna. Bukan kekasihnya–seorang penyair–yang membuat aku tak bisa melupakan cerita itu, melainkan puisinya. Puisi itu ditulis di dada temanku oleh kekasihnya sebagai hadiah ulang tahun. Tentu saja temanku sangat bahagia. Sampai terakhir bertemu, lima bulan lalu, perihal puisi itu masih tetap menjadi perbincangan kami. Semangatnya bercerita juga masih sama dengan kali pertama ia bercerita. Begitu pula aku, juga tak kalah semangat mendengarkannya.
Temanku itu kemarin baru saja menikah. Suaminya tentu saja kekasihnya yang menuliskan puisi di dadanya itu. Ia mengabariku lewat pesan melalui facebook, yang belum sempat aku ceritakan padamu. Mungkin kau bertanya-tanya mengapa aku menceritakan kisah cinta temanku di saat kita sedang menikmati pertemuan untuk membunuh rindu yang telah lama meraung-raung dalam hati. Terlebih kisah itu sangat berlawanan dengan kisah kita.
Aku sendiri tak tahu mengapa aku melakukannya. Aku tidak terlalu bahagia mendengar temanku menikah. Aku lebih tertarik pada cerita itu daripada kabar pernikahannya. Bagaimana denganmu? Apa kau juga menyukai cerita itu? Suka atau tidak, aku akan tetap meneruskan ceritaku sambil sesekali memagut dalam-dalam bibirmu.
“Kau masih mendengarku, Baruna?”
“Ini adalah peristiwa langka. Jadi aku akan mendengarnya hingga usai”.
Setelah pernikahan temanku satu bulan lalu, cerita itu semakin terngiang-ngiang di telingaku. Bayangan puisi itu menari-nari di depan mataku. Aku seperti bisa melihat jelas bagaimana kekasihnya itu pelan-pelan mulai menggoreskan tinta di dada temanku. Saat seperti ini, kau seharusnya ada di sampingku, sehingga imajinasiku tidak berkelana sendiri. Aku ingin kau juga melihat proses penulisan puisi itu. Ah, aku mulai merasa senang dengan pernikahan temanku. Betapa bahagianya dia, bisa memiliki suami seorang penyair.
Kebahagiaan itu saat ini dapat aku lihat dengan jelas, Baruna. Puisi di dada temanku itu tak pernah kesepian. Kekasih yang saat ini menjadi suaminya selalu mengunjungi puisi itu setiap hari. Aku mulai iri dengan temanku itu.
“Apakah kau tak ingin seperti kekasih temanku itu Baruna? Jika puisi itu telah kau tulis, aku ingin kau mengunjunginya setiap hari.” Itu pertanyaan yang aku ajukan padamu setelah aku mendengar kisah temanku. Kau tak langsung menjawab. Keesokan harinya kau lalu mengajakku pergi ke sebuah telaga. Aku tidak akan pernah lupa peristiwa itu.
Waktu itu aku dan kau duduk di tepi telaga. Suasananya masih begitu sepi karena hari masih terlalu pagi. Pohon trembesi di sekitar telaga tengah tersapu kabut. Pohon pinus di bukit-bukit yang mengitari telaga masih samar dalam pandangan. Permukaan telaga bagai bertirai garis-garis hujan. Ketika hujan mereda, tiba-tiba aku teringat cerita temanku tentang sebuah puisi dan kekasihnya itu. Sungguh, cerita itu sangat berkesan bagiku. Lalu aku melempar tanya lagi, “Maukah kau menulis sebuah puisi untukku?” Baruna mengalihkan pandangannya dari tengah telaga berpindah ke wajahku. Lelaki itu balik bertanya, “Kau mau aku menuliskannya di dadamu?”
Wajahku memancarkan semburat merah dengan hiasan senyum malu. Belum sempat aku menjawab pertanyaanmu, kau lebih dulu melumat bibirku. Hanya sekilas. Lalu kau mengulangi pertanyaanmu, “Kau mau aku menuliskannya di dadamu?” Aku mengangguk.
“Tulislah puisi itu di sini, Baruna,” Aku menunjuk dadaku.
“Baiklah. Aku akan melakukannya. Hanya untukmu”.
Aku duduk menghadapmu. Kedua kakiku kulipat ke belakang. Rambutku yang menutup dada aku sibakkan ke belakang pula. Tak kubiarkan sehelai rambutpun menghalangimu menulis puisi di dadaku. Sementara kau masih sibuk menyiapkan semua perkakas yang kau perlukan. Seperangkat hati, pena cinta, lalu apalagi? Hanya itu yang kau katakan padaku, Baruna.
Kancing kemeja merah muda yang menutup dadaku sudah keluar dari lubangnya masing-masing. Lima menit berlalu. Tak ada sehelai kainpun menutup dadaku. Aku tak sabar ingin melihat kau menulis puisi itu. Kupejamkan kedua mataku. Kemarin aku hanya mendengar cerita tentang puisi yang ditulis di dada seorang perempuan dari temanku. Namun, kini aku menyaksikannya secara nyata. Bahkan akulah tokoh utamanya. Aku menunggumu dalam kepasrahan. Kutahan kuat-kuat degup jantungku yang semakin cepat berdetak. Kututup rapat-rapat rasa cemas yang melintas dipikiranku.
“Ayo, Baruna, aku sudah tak sabar,” kataku tanpa membuka mata sedikitpun.
Aku tak tahu mengapa Baruna tak juga mulai menuliskan puisinya di dadaku. Mungkin ia masih berpikir bagaimana dan darimana mulai menuliskannya. Ia memang terbiasa menulis puisi, namun kali ini beda. Sebelum aku dan Baruna berada di kamar ini, pastinya ia telah memikirkan banyak hal tentang bagaimana menulis puisi di dada perempuan. Aku mau Baruna hanya akan melakukan hal ini sekali dalam seumur hidupnya.
“Jangan pikirkan bagus tidak puisinya, yang penting tanganmulah yang menuliskannya. Kali ini dadaku adalah kertasmu. Menulislah semaumu”.
Ayolah Baruna. Tunggu apalagi? Rajukku mulai tak sabar. Aku khawatir tak sanggup lagi menahan gemetar, tak kuasa lagi mendekap rasa cemas.
Baruna mulai bergerak. Ditariknya nafas dalam-dalam lalu dihembuskanya perlahan-lahan. Mungkin itu untuk menenangkan dirinya. Sekarang aku akan memulainya, Baruna berbisik ke telingaku. Dengan hati-hati kau mulai menggoreskan pena di dadaku yang licin. Aku tersenyum. Huruf demi huruf kau tulis pelan. Sesekali kau hapus, entah menggunakan apa, rasanya dingin. Kadang kau berhenti sejenak. Dengan mata terpejam aku mencoba mengeja tulisanmu. Sia-sia. Aku tak bisa, yang muncul hanyalah wajahmu Baruna.
“Ini akan segera selesai. Namun, aku enggan untuk mengakhirinya. Aku ingin terus memandangnya,” bisiknya padaku.
Kubuka mataku sambil kulemparkan senyum pada Baruna. Itu tak lama. Kau mulai menulis lagi. Aku memejamkan mata lagi. Aku sekarang tahu mengapa temanku terlihat begitu bahagia ketika menceritakan kekasihnya dan puisi.
Aku masih memejamkan mata.
“Belum selesai juga?” tanyaku pada Baruna.
Ia tak segera menjawab. Dan aku masih terus memejamkan mata tanpa tahu apa-apa. Baruna berbisik ke telingaku, Jangan buka matamu. Aku masih ingin membaca ulang puisi yang kutulis di dadamu. Aku hanya mengangguk.
Bukalah matamu sekarang.
Kubuka mataku pelan-pelan. Senyummu menyambutnya. Kulihat keringat menetes dari wajahmu. Kau pasti menuliskannya dengan seluruh tenagamu. Bergegas kualihkan pandanganku ke dadaku. Kueja kata demi kata yang kau tulis.
Ah, aku mulai berimajinasi. Pikiranku berkelana pada masa silam. Maafkan aku. “Kau sudah tidur Baruna?”
Tak ada suara. Aku tahu kau sudah tertidur. Namun, seperti kataku di awal tadi. Aku akan tetap bercerita meskipun kau tertidur. Aku akan bercerita hingga malam habis, Baruna. Sebab aku tahu, setelah ini kita tak mungkin bertemu lagi. Mau tidak mau pada akhirnya kita harus menghadapi sesuatu yang paling kita takutkan–waktu–. Waktu tidak akan memihak kita. Waktu tak lagi memberi kesempatan kita untuk bersama. Aku akan menikmati malam terakhir sebelum laki-laki itu menyebut aku sebagai istrinya. Lalu setelah itu, kita akan menutup kisah. Saling melupa.
Waktu berjalan begitu cepat malam ini. Satu jam lagi pagi akan segera datang Baruna. Karena itu, aku akan segera menutup ceritaku tentang puisi di dada temanku, sebelum kita mencapai titik puncak sebuah kesepakatan untuk tak saling menghubungi apalagi bertemu demi kebaikan bersama. Kita harus mengubur dalam-dalam sebuah kisah masa lalu yang indah itu. Seperti katamu, penyelesaiannya semua kembali pada diri masing-masing.
Sebenarnya aku ingin kau mendengar akhir ceritaku, Baruna. Sayangnya kau telah tidur. Tapi tak apa, aku akan meneruskan ceritaku sambil memandang wajahmu untuk yang terakhir.
Baruna, kisah yang kuceritakan itu sebenarnya tidak pernah ada. Teman yang bercerita padaku itu hanya imajinasiku saja. Tentunya tidak ada temanku yang menikah kemarin. Tak ada pula puisi yang di tulis di dadanya. Tak ada penyair pastinya. Kau pasti tahu mengapa aku suka membuat kisah tentang penyair dan puisi bukan?
Kalau saja boleh, aku ingin kau menengok kembali puisi yang sempat kau tulis di dadaku waktu itu, satu-satunya puisi yang kautulis di dada seorang perempuan. Karena itu, bisakah kau bangun sebelum pagi tiba? Jawablah Baruna!
***
Baruna terbangun dengan selembar kertas di sampingnya. Sepi, yang terdengar hanyalah detik jam dinding yang menunjuk angka tujuh. Baruna mengambil kertas itu dan membuka lipatannya. Sebuah tulisan singkat. Baruna membacanya.
Baruna, jika ada waktu tengoklah puisi yang kautulis di dadaku agar ia tak kesepian.
Dengan tergesa Baruna mengambil ponselnya untuk menghubungi perempuan penulis pesan itu. Baruna terperanjat. Ada panggilan tak terjawab lima menit lalu. Ia lalu menelpon balik. Nomor yang dituju tidak aktif. Baruna memerhatikan waktu yang terpampang di ponselnya. Jam 07.10 pagi. Kesepakatan kemarin mereka akan berpisah tepat jam 6 pagi. Baruna menyesal mengapa ia tertidur semalam. Kini ia terlambat. Satu jam yang lalu perempuan itu telah pergi. Air membendung di mata Baruna. Perempuan itu telah meninggalkannya dan kembali ke rumah untuk mempersiapkan pernikahannya.
Dengan perasaan tak menentu, Baruna kembali ke tempat tidur sambil memeluk erat-erat kertas yang berisi pesan perempuan itu. Ia diam sesaat. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara yang berasal dari ponselnya. Ia mengambil dan menyentuh layarnya. Sebuah pesan. Baruna membukanya.
Mas kapan pulang? Putri kecilmu terus menangis mencarimu.
Baruna tak membalasnya. Ia cepat-cepat membuka baju yang melekat di tubuhnya lalu menuju kamar mandi. Ia harus segera pulang. Ada perempuan mulia yang menunggunya dan seorang putri cantik yang menunggu digendongnya.
***
Sri Wahyuni, tim Sekolah Literasi Gratis (SLG) 2 STKIP PGRI Ponorogo.
Sumber: https://ideide.id/puisi-di-dada-temanku.html

