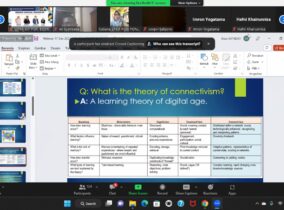Dosen STKIP PGRI Ponorogo Beberkan Rekaman Pelanggran HAM di Event Internasional

Dosen STKIP PGRI Ponorogo, Arafat Nur membeberkan rekaman pelanggran HAM yang terjadi di Aceh pada event internasional, yaitu di Jakarta Content Week (Jaktent) 2021 Program Literary Festival, Rabu 10 November 2021.
“Saya, selaku orang yang menyaksikan dan mengalami langsung sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang diakibatkan dari dua kelompok yang bertikai di Aceh, sampai sekarang tidak bisa melupakannya dan masih menyisakan rasa sakit di jiwa dan hati saya,” ungkapnya di sesi Every Thursday acara tersebut.
Lebih lanjut Arafat Nur mengemukakan, sejumlah peristiwa yang dialaminya itu meninggalkan lubang dalam di dalam dirinya. Lubang yang merupakan trauma berat masa lalu yang tidak kunjung bisa ditutup. Dan sepertinya akan selamanya tidak bisa tertutup, dan tidak bisa sembuh.
Beberapa peristiwa ngeri yang hampir membuat dia terbunuh, baik ketika dia terperangkap dalam sebuah baku tembak, pelemparan bom di sekitar tempatnya bermalam, hingga diculik ke sebuah hutan di pinggir sungai untuk menghabisi dirinya. “Seandainya tidak ada suatu kejaiban yang membuat saya terbebas dari semua itu, tentu saja saya sudah mati, puisi-puisi, cerpen-cerpen, dan novel-novel saya tidak akan pernah ada seperti sekarang,” ungkapnya.
Dia ingat, peristiwa pertama yang menguncang hidupnya sekitar 1999. Ketika itu usia dia berusia 23 tahun. Dia tinggal di sebuah bilik (kamar) tua di sebuah dayah (pesantren tradisional) di Desa Rhieng Blang, Meureudu, Pidi Jaya, Aceh. Dia tidak tahu pada subuhnya sekelompok pejuang Aceh Merdeka menghadang tiga truk reo pasukan tentara RI yang melintasi jalan di sana. Kelompok pejuang melepaskan senjata pelontar ke arah truk yang membuat banyak tentara pemerintah tewas. Ada yang menyebut 25 tentara tewas, namun pihak tentara mengakui hanya lima personil mereka yang tewas.
Nah, bias atau ekses setelah peristiwa itu membuat penduduk di tiga desa dekat TKP mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia melihat langsung ribuan pasukan tentara masuk kampung, mengumpulkan semua penduduk laki-laki, tua-muda, lalu digiring merangkak di aspal panas menuju ke lapangan dan kantor polisi di kecamatan yang jaraknya lebih dari 1 km. Tidak seorang pun diperbolehkan jalan tegak.
Sambil merangkak, lelaki tua-muda ditendangi, kepala dipukuli, punggung diinjak-injak. Lantas berlanjut penganiayaan berat di halaman dan jalan kantor polisi setempat. Kata Arafat, selain lutut yang luka-luka, wajah lembam-lembam, rusuk dan kaki patah, banyak lagi cedera yang dialami penduduk sekitar. Dia melihat keadaan mereka baru beberapa hari kemudian. Sebab, sebelum tentara mengumpulkan dan menyiksa penduduk di sana, dia sudah lebih dulu menyelamatkan diri, lari dengan meminjam sepeda ontel milik ustaznya.
Ketika itu Arafat Nur mendapatkan firasat buruk, bila tidak lari dari sini secepatnya, dia bakalan mengalami penyiksaan serupa. Begitu melihat pasukan tentara masuk dengan berjalan kaki, dia segera bergegas memasukkan semua pakaian dan barang-barang ke dalam kardus, lantas mengikatnya di boncengan sepeda ontel yang dia pinjam, setelahnya dia langsung mendayung secepat mungkin ke arah laut karena itulah satu-satunya jalan yang belum dikuasai tentara.
Dia pun melalui jalan setapak untuk berlari sejauh-jauhnya dari desa itu hingga kemudian tiba di Ulim, kota kecamatan tetangga. Dia pun menginap di rumah seorang penduduk di sana. “Dua hari kemudian, saya kembali lagi ke bilik dayah. Yang membuat saya heran, sepanjang jalan yang saya lalui kosong, tidak ada seorang pun di jalan. Dayah saya tinggali juga kosong. Tidak ada Ustaz Amir dan istrinya, padahal saya berniat untuk mengembalikan sepeda,” kisahnya.
Akhirnya Arafat Nur pergi ke Masjid dan sebuah gedung SD Beuracan. Rupanya, semua penduduk sudah mengungsi ke sana. Di sana dia mendengar orang-orang bercerita berbagai peristiwa saat ratusan tentara menyiksa penduduk yang membuatnya semakin ketakutan. Apalagi setelahnya dia melihat banyak lelaki cedera parah dan terpaksa menjalani perawatan.
Waktu itu sastrawan yang telah dua kali memenangkan sayembara novel DKJ ini sudah mulai menulis puisi, cerpen, dan artikel di koran Serambi Indonesia terbitan Banda Aceh dan harian Waspada terbitan Medan. Karena suntuk dan tidak tahu apa yang mesti dia buat di pengungsian, dia pun menulis puisi, terkadang cerpen. “Namun, kemudian saya dicurigai oleh kelompok GAM Pimpinan Teungku Don bahwa saya ini mata-mata serdadu pemerintah. Saya pun ditangkap, ditutup matanya, dan dibawa ke sebuah hutan di Alue Awe,” paparnya.
Di sebuah pos di pinggir sungai yang hening, dia melihat sejumlah lelaki bersenjatakan laras panjang. Salah seorang menggeledahinya, dompetnya diperiksa, kemudian dia disuruh berdiri di pinggir sungai. “Mungkin seseorang sudah siap menembak punggung saya ketika itu. Mungkin hari itu juga saya mati. Kalau saya mati hari itu, tentu saja saya tidak lagi bisa menulis puisi, cerpen, novel, dan berbicara di LitFest Jaktent Content Week 2021 ini,” ucapnya dengan nada getir yang mengandung gurauan.
Seorang lelaki dari Lembaga HAM yang datang kemudian menyelamatkan Arafat Nur sebelum lelaki bersenjata laras panjang sebelum sempat menembak kepalanya. Setelah terjadi nego beberapa lama dan orang HAM itu menjaminnya, akhirnya mata Arafat ditutup kembali dan dipulangkan ke pengungsian. Setelah tidak lama berada di pengungsian, dia pun melarikan diri ke Banda Aceh, dan hidup luntang-lantung di sana, lapar-lapar kenyang karena tidak ada uang dan pekerjaan.
Dalam acara tersebut Arafat Nur tampil bersama dua penulis lain, yaitu Aprila Wayar dan Awi Chin, dimoderatori oleh F.X. Baskara T. Wardaya. Arafat Nur sendiri adalah korban perang Aceh, penulis puluhan novel sastra yang mendapatkan sejumlah perhargaan bergengsi dan kerap diundang dalam event-event internasional. Novel-novelnya sangat kuat, berkisah tentang kekejaman militerisme dan kesengsaraan rakyat Indonesia yang tertindas. Dua novel di antaranya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kini dia mengabdikan diri sebagai pengajar di STKIP PGRI Ponorogo, Jawa Timur. [] Red/ Humas